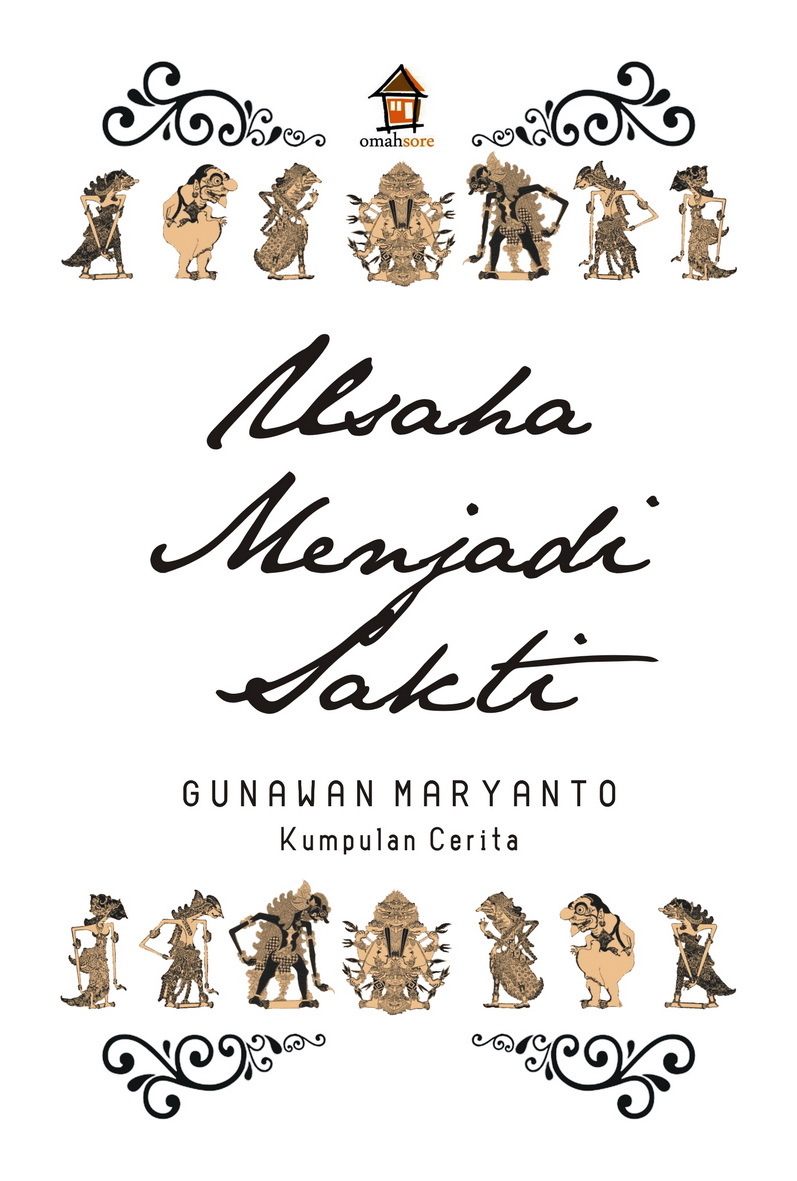
Setelah gagal memperoleh kesaktian dengan jalan bertapa di kebun belakang rumah, aku jadi tak banyak bicara. Hanya Budi yang tahu kesedihanku. Dia pula satu-satunya orang yang tahu bahwa aku pernah bertapa di bawah pohon melinjo yang kelak tumbang berbarengan dengan meninggalnya ibuku. Tak perlu kuceritakan bagaimana jalannya samadiku yang pertama dan terakhir itu. Yang terang tak sehening Begawan Ciptoning di cerita wayang. Tak ada setan atau bidadari yang menggoda dan duduk di pahaku. Tak ada Narada atau Jibril yang datang membawa wahyu. Cuma sejumlah semut rangrang, menggigitku berulang-ulang. Seminggu setelah kegagalan itu, Budi datang membawa kabar bahwa Antok, anak pawang ular yang tinggal ujung timur kampung, telah mengangkat dirinya menjadi guru. Aku tak terlalu mengenalnya meski sebenarnya jika dirunut-runut kami masih bersaudara. Nenek Antok, kami biasa memanggilnya Mbah Dukun, dan Nenekku, Mbah Dukuh Lawas, memiliki ikatan persaudaraan, entah bagaimana persisnya pertalian itu. Budi meyakinkanku bahwa kami bisa diterima menjadi muridnya. Kata Budi telapak tangan kanan Antok seperti mata air. Tiap kali haus Antok tinggal menempelkan telapak tangannya ke bibir. Aku tak sepenuhnya percaya tapi saat itu juga kami segera mencarinya. Aku lupa apakah kami berhasil menemuinya sore itu atau tidak. Ada beberapa bagian yang hilang, memang, dari kisah ini—semoga tak terlalu mengganggu.
Author
